PERUBAHAN IKLIM yang ditandai dengan mencairnya bukit-bukit es di kutub, telah pula dirasakan di Provinsi Jambi. Ini ditandai dengan musim yang bergeser hingga meningkatnya suhu di sekitar kita. Satu hal yang diyakini sebagai penyebabnya adalah menurunnya luasan tutupan hutan. Walau tak tertutup kemungkinan disebabkan oleh pertambahan penduduk di sebuah wilayah. Selain menyebabkan “dibukanya area hijau”, pertambahan penduduk memberikan pengaruh yang kompleks, seperti polusi. Dikarenakan asap dari berbagai bahan bakar fosil, yang keluar dari knalpot kendaraan, dan juga cerobong asap pabrik. Termasuk pula kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi hampir setiap tahun, sejak era ’90-an. Yang sangat berhubungan dengan pembukaan areal perkebunan sawit, diakui atau tidak.
Situasi di atas, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, telah membuat Indonesia dan rakyatnya masuk ke dalam pusaran carbon trade. Yang secara riil telah membuka ruang bahwa pohon tidak hanya bernilai ekonomis pada kayunya. Tapi juga pada kemampuan pohon untuk menyerap karbon, yang selama ini dihitung dengan sistem per metric cubic ekuivalen atau setara dengan USD6 hingga USD12.
Data Kementerian Pertanian mencatat, lahan tutupan sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2019, yakni 1.134.640 hektare atau sekitar 6,93 persen dari total luas tutupan sawit nasional. Sementara itu, luas areal karet di Provinsi Jambi pada 2019 tercatat 390.707 hektare.
Hutan, dengan arti yang luas, sebut saja “area konservasi”. Atau, area yang “berwarna hijau” dengan biodiversity (keanekaragaman hayati).
Tentunya, Provinsi Jambi adalah area yang berhubungan dengan climate change. Sebab semakin berkurang tutupan hutan di sini, akan berpengaruh juga dengan mencairnya bukit-bukit es di kutub tadi.
Cukup menarik jika melirik data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI yang menyebutkan tutupan hutan di Provinsi Jambi pada tahun 2019 lalu hanya tersisa seluas 882.272 hektare. Padahal, pada 10 tahun lalu tercatat sekitar 1,3 juta hektare. Mari diperbandingkan dengan data dari Kementerian Pertanian tadi. Sekadar informasi, luas total Provinsi Jambi adalah 50.160,05 kilometer persegi. Selain tutupan hutan, terdapat juga “area yang tidak terawat”, yang biasa disebut dengan “lahan kritis”. Yakni area yang telah ditebang (logging), dibuka (land clearing), atau digali untuk pertambangan.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total luasan hutan dan lahan kritis di Provinsi Jambi hingga 2019 lalu, mencapai 844.647 hektare. Hutan dan lahan kritis ini tidak hanya berada di kawasan hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung, konservasi dan taman nasional. Sangat mudah untuk mengetahui mana area yang rusak atau kritis, dan mana yang masih baik. Yakni dengan melihat kehidupan lebah madu. Koloni lebah sangat membutuhkan sari bunga atau buah, untuk dihasilkan menjadi madu. Area yang masih baik, akan dihidupi oleh koloni lebah.
Sedangkan area yang kritis, yang tidak lagi memiliki pohon, tidak akan dijadikan area kehidupan bagi koloni lebah. Sebab tidak ada lagi sari bunga dan buah yang akan dihisap lebah pekerja untuk dijadikan madu. Area yang terkategori kritis sudah seharusnya dilihat dalam kerangka perdagangan karbon (carbon trade). Cara yang dianggap ampuh, adalah dengan revegetasi; yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan nilai karbon saja, tapi juga pada perbaikan lingkungan dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Secara umum, revegetasi adalah proses penanaman kembali dan pembangunan kembali terhadap area tanah yang terganggu. Proses ini, bisa saja melalui proses alami, ataupun tindakan yang dilakukan oleh manusia. Banyak cara untuk memperbaiki kualitas fisik tanah yang terkategori kritis. Satu diantaranya adalah perkebunan monokultur, atau bahkan pertambangan. Yang banyak terjadi saat ini adalah pertambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka (open pit).
Setelah batu bara di keruk, maka sudah seharusnya dilakukan reklamasi. Reklamasi dapat diartikan dengan menutup kembali area eks tambang yang terbuka. Jika berbicara kondisi Provinsi Jambi saat ini, kerusakan “area hijau” tidak hanya terjadi karena aktifitas pembalakan liar (illegal logging) di bawah era 2000-an saja. Seperti diketahui, aktivitas liar itu kemudian berubah bentuk menjadi “land clearing”.
Reklamasi, atau rehabilitasi lahan (hutan) yang terdegradasi adalah bagian dari agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) di Rio de Janerio pada tahun 1992 lalu. Jika bicara tentang revegetasi, banyak yang memilih untuk menggunakan varietas endemik. Seperti bulian, mersawa dan tembesu. Pilihan ini karena terkait dengan nilai ekonomis dari kayu tadi. Namun, tentu butuh waktu yang lama untuk bertumbuh. Sementara kawasan yang telah rusak itu seharusnya segera “digarap” dalam perspektif pemenuhan permintaan carbon trade.
Bahkan, jika benar menguntungkan secara ekonomi, area di perkotaan yang selama ini menjadi kawasan konservasi, sempadan sungai, pinggir jalan dan ruang terbuka pun dapat bernilai ekonomi tinggi untuk dilihat melalui kacamata perdagangan karbon. Selain varietas tadi, terdapat pilihan lain yang dapat tumbuh dengan cepat dan dapat bertahan hidup di area yang kritis. Beberapa pilihan, adalah; pinus, sengon dan akasia, yang dapat dibandingkan dengan pohon buah seperti durian, rambutan dan mangga.
Dalam menghadapi perubahan iklim, kita semua berpacu dengan waktu. Perubahan iklim wajib dikendalikan. Jika kita tidak berlari kencang, mencairnya bukit-bukit es di kutub bisa menyebabkan banjir yang mungkin lebih dahsyat dari banjir di zaman Nabi Nuh. Bumi terancam tenggelam! ***





















































































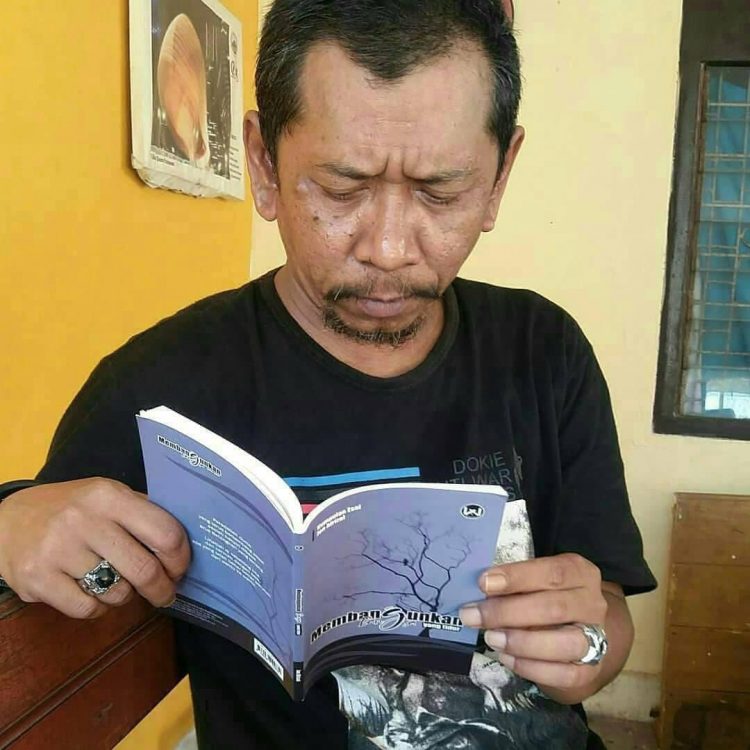




















Discussion about this post